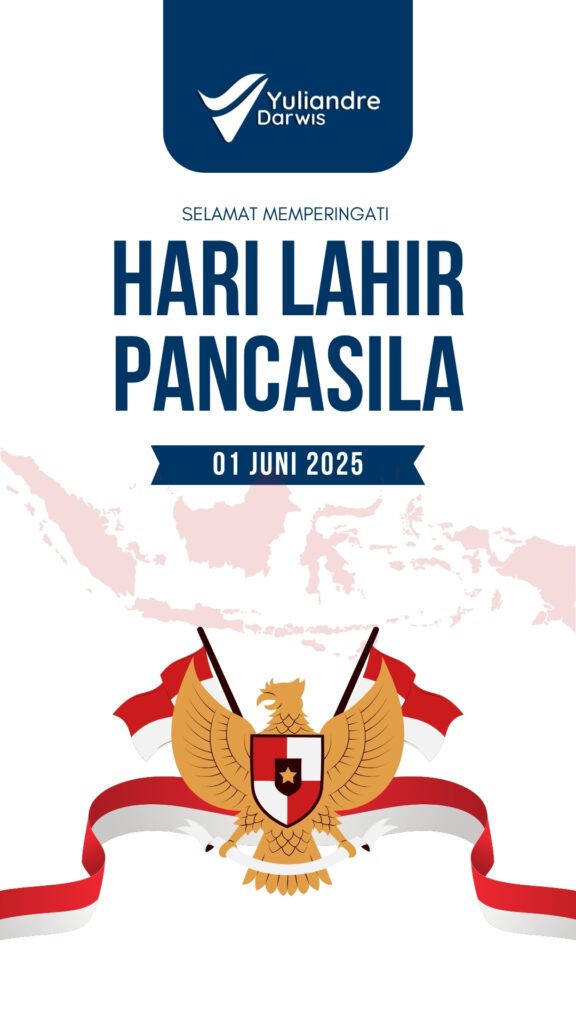Setiap 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan utama kita bukan hanya menjaga ideologi, tapi juga mengomunikasikannya secara relevan, inklusif, dan membumi. Sebab, ideologi yang tidak dikomunikasikan dengan cara yang menyentuh hati rakyat, lama-lama akan terasa asing, bahkan bisa kehilangan makna.
Sebagai putra Minangkabau, saya percaya bahwa Pancasila bukan sekadar warisan nasional, tapi juga selaras dengan nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Konsep “raso jo pareso” dalam budaya kita, sejatinya adalah wujud hidup nilai-nilai seperti kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial, tiga sila yang kini makin diuji di tengah komunikasi publik yang cenderung rumit dan berpolarisasi.
Hari ini, kita hidup dalam era algoritma, bukan lagi era ideologi. Narasi-narasi viral lebih sering ditentukan oleh emosi, bukan substansi nilai. Maka, tugas kita sebagai komunikator bangsa adalah mengemas ulang Pancasila dalam bahasa yang bisa dimengerti generasi digital namun tanpa kehilangan kedalaman makna. Bukan dengan jargon, tapi dengan cerita; bukan dengan poster, tapi dengan empati.
Di tanah Minang, warisan lisan seperti kaba, tambo, atau pantun petatah-petitih adalah contoh nyata bahwa komunikasi bernilai tidak selalu harus modern. Kita bisa menjadikan warisan ini sebagai media edukasi ideologis yang membumi dan merakyat.
Industri kreatif di Sumatera Barat, termasuk komunitas film lokal, podcast, dan konten kreator muda, punya peluang besar menjadikan Pancasila sebagai ruh narasi. Konten kebangsaan tidak harus kaku, asal jujur dan otentik, pasti akan hidup. Inilah yang disebut sebagai komunikasi ideologis yang lentur, bukan hanya sekedar teori.
Momentum Hari Lahir Pancasila ini semestinya bukan hanya untuk mengulang pidato-pidato besar, tapi menjadi panggilan bagi kita untuk membumikan Pancasila secara kreatif dan kontekstual, termasuk dari Minangkabau untuk Indonesia.
Sebab dalam raso jo pareso itu kita belajar bahwa nilai tidak hanya ditanamkan lewat kata, tapi juga lewat rasa. Dan rasa itu hanya tumbuh kalau komunikasi kita menyentuh akar budaya, akar sosial, dan akar kebangsaan itu sendiri.